Sehubungan dengan artikel Bapak di harian Kompas, 28 Juli 2012, yang berjudul Kemiskinan dan Pengangguran, perkenanlah kami memberikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut:
1. Bapak menulis: “Almarhum Hartojo Wignjowijoto, ekonom jebolan Harvard, sering melempar cemohan ”there are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics”—ada tiga macam kebohongan: bohong, serba bohong, dan statistik.”
Tanggapan saya: Saya menyayangkan gaya bahasa Bapak yang seolah-olah mengatribusikan kutipan ”there are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics” tersebut sebagai milik almarhum Hartojo Wignjowijoto. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada almarhum, kutipan itu jelas-jelas tidak mungkin diatribusikan ke almarhum Hartojo Wignjowijoto, mengingat beliau baru lahir pada 5 Juli 1936 sementara kutipan itu sendiri telah beredar secara luas pertama kali dalam Chapters from My Autobiography”-nya Mark Twain tahun 1906 yang mengacu ke Benjamin Disraeli (1804–1881):
I was deducing from the above that I have been slowing down steadily in these thirty-six years, but I perceive that my statistics have a defect: three thousand words in the spring of 1868, when I was working seven or eight or nine hours at a sitting, has little or no advantage over the sitting of to-day, covering half the time and producing half the output. Figures often beguile me, particularly when I have the arranging of them myself; in which case the remark attributed to Disraeli would often apply with justice and force:
“There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.”
Mengacu ke autobiografi Mark Twain itulah, sebagian besar orang termasuk http://www.quotationspage.com mengatribusikan kutipan ini sebagai milik Benjamin Disraeli, meski pun dibantah oleh artikel ini dan ini. Saya berhusnudzon Bapak menulis kalimat ini untuk menghormati almarhum ekonom Hartojo Wignjowijoto, dan bukan untuk mengatribusikan kalimat tersebut sebagai milik beliau.
2. Bapak menulis: “Miskin bukan lagi persoalan keberadaan pada garis atau di bawah garis kemiskinan yang dibuat ekonom dan statistikus konvensional.”
Saya sudah mengecek ke situs Kamus Besar Bahasa Indonesia online milik Kemendiknas di sini, dan tidak ditemukan kata statistikus sebagai suatu kata. BPS sendiri sebagai gudangnya statistician justru menggunakan kata statistisi Pak, bisa dicek di Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 Tentang Jabatan Fungsional STATISTISI dan Angka Kreditnya.
3. Bapak menulis: “Miskin bukan lagi persoalan keberadaan pada garis atau di bawah garis kemiskinan yang dibuat ekonom dan statistikus konvensional.”
Bapak memberi contoh atas pemikiran ini dengan kasus-kasus sebagai:
- Seseorang terpojok miskin tatkala ia melihat iklan-iklan di televisi menayangkan kemewahan yang tidak terjangkau daya belinya. Gebyar-gebyar kemewahan mengepung kemiskinannya, yang menjadikan nestapa dalam keperihan hati.
- Pegawai-pegawai negeri dan swasta pun menjadi miskin oleh iklan-iklan rumah dan apartemen mewah metropolitan yang menggugah kecemburuan sosial dan menumbuhkan ”minderisasi” (inferiorization), sementara cicilan rumah sederhana mereka menjadi beban berkepanjangan.
- Bapak menulis: Seorang dosen bisa ”termasuk miskin” meskipun gajinya Rp 2,4 juta, ia keluarkan untuk pekerja rumah tangga (PRT) Rp 750.000, listrik Rp 500.000, iuran RT/RW Rp 200.000, cicilan laptop, pulsa, dan tetek-bengek.
Menurut saya sih, contoh-contoh di atas lebih cocok disebut sebagai cash mis-management atau expense mis-management. Sebagai seorang guru besar di universitas terkenal di Indonesia tentu sudah paham pertanyaan mendasar dasar dalam ilmu ekonomi, how do we satisfy unlimited wants with limited resources? Kalau dengan sumber penghasilan Rp2,4 juta/Rp250 ribu, pengeluaran berapa sih yang paling sesuai dengan kebutuhan? Apa prioritas yang sangat perlu, perlu, kurang perlu, dan tidak perlu sama sekali? Kalau semua keinginan pengen dipenuhi mah, sampe kapan juga semua orang bisa disebut miskin, Pak.
Agak kurang pas kalo ego pengeluaran dan konsumerisme ini lantas dikaitkan dengan tingkat kemiskinan. Agak kurang pas juga kalo seseorang dengan penghasilan Rp2,4 juta tetap mengaku miskin karena pengeluarannya lebih besar dari penghasilannya. Inilah sepertinya yang membuat semua pos subsidi untuk “masyarakat miskin” di Indonesia jarang tepat sasaran karena semua orang rela disebut sebagai orang miskin dapat mendapatkan beras miskin, bantuan sosial, dan bahkan subsidi BBM.
Lagian Pak, iuran RT/RW-nya mahal banget Pak, koq sampe Rp200 ribu sih? Lagian itu rumah segede apa dan dipasang berapa AC sampe tagihannya Rp500 ribu? Dan masih perlu dianggap miskin juga? ck..ck… Relatif ke sesama orang lain yang kurang beruntung, deskripsi pengeluaran seperti ini lantas masih (perlu) dianggap miskin mah keterlaluan, Pak. 😦
4. Bapak menulis: “Pembangunan dengan semangat pasar bebas dan perdagangan bebas yang memiskinkan kehidupan dan melumpuhkan semangat hidup rakyat harus distop.”
Seandainya Bapak punya kajian tentang dampak dari pasar bebas dan perdagangan bebas yang memiskinkan kehidupan dan melumpuhkan semangat hidup rakyat, tolong saya dikasi tau Pak. Saya bingung, emang bagian mana dari pasar bebas dan perdagangan bebas (kalau pun iya Indonesia emang bener-bener melaksanakan pasar bebas dan perdagangan bebas), yang bikin rakyat miskin tambah repot. Argumen saya:
- Kerajaan Sriwijaya di Palembang pada abad ke-13 tidak menjadi besar dan jaya dengan menutup diri dari pedagang-pedagang Cina, Arab dan Eropa, tapi justru dengan berinteraksi, berdagang, dan membuka diri terhadap pihak luar. Begitu juga kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lampau, mereka berjaya justru dengan berinteraksi dengan pihak luar.
- Bahwa para petani dan penggarap hasil bumi utama di masa lampau (lada, pala, cengkeh, dll.) tidak pernah merasakan kesejahteraan dari perdagangan bebas justru karena pengaruh raja-raja lokal yang menguasai semua hasil produksi dan menjualnya ke pedagang atau penjajah. Itu juga yang, menurut saya, masih terjadi sampe sekarang.
- Bahwa dengan perdagangan bebas dengan pihak luar kita akan tahu apa yang paling efisien untuk dilakukan oleh orang Indonesia. Apakah lebih efisien untuk mengimpor kedelai atau menanamnya sendiri, misalnya.
- Justru dengan mengimpor buah jeruk Mandarin murah, sepatu, mainan, dan tetek bengek murah meriah lainnya dari China lah masyarakat miskin dapat mengoptimalkan pengeluarannya.
- Perdagangan bebas memang akan sangat merugikan produsen yang tidak efisien dalam produksinya sehingga perlu perlindungan dan subsidi dari negara atau konsumen.
Demikian kami sampaikan,
Hormat saya,
MAMAN FIRMANSYAH

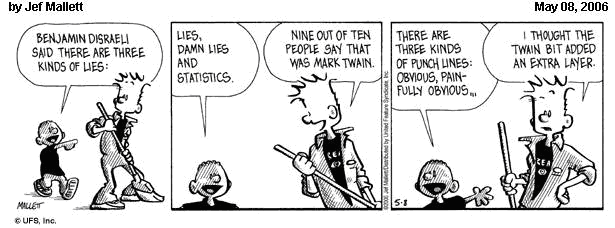
 A father, a husband, and an employee. I am spending my precious notworking time by browsing, blogging, reading books, and taking care of my little daughter. Complete profile could be seen
A father, a husband, and an employee. I am spending my precious notworking time by browsing, blogging, reading books, and taking care of my little daughter. Complete profile could be seen